Oleh: Eka Mariya Cahyadi
“Manusia hidup berkelompok dalam permukiman yang layak wajib memenuhi standar fasilitas. Permukiman kumuh ditandai bangunan, akses, air, drainase, limbah, sampah, dan proteksi kebakaran buruk, butuh partisipasi masyarakat”
Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami memiliki kecenderungan untuk hidup dan menetap secara berkelompok atau komunal dalam suatu lingkungan. Lingkungan tempat tinggal atau hunian bagi manusia ini dikenal sebagai kawasan permukiman, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tinggal di permukiman layak huni yang mampu memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, serta nyaman melalui terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang.
Kawasan permukiman layak huni harus memenuhi standar fasilitas dan kondisi yang menunjang kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, apabila lingkungan permukiman tidak memenuhi standar tersebut, kawasan itu disebut sebagai permukiman kumuh. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 telah menetapkan tujuh kriteria untuk mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh sebagai berikut:
Kriteria Permukiman Kumuh
Pertama, Bangunan Gedung. Kekumuhan terlihat dari ketidakteraturan bangunan, kepadatan yang tinggi, dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Ketidakteraturan terlihat dari letak dan penampilan bangunan yang tidak sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Kepadatan berlebihan mengacu pada jumlah bangunan yang melebihi ketentuan yang berlaku. Bangunan dengan konstruksi atap, alas, dan dinding yang rusak atau tidak kokoh juga termasuk kondisi kumuh.
Kedua, Permukiman kumuh ditandai dengan tidak adanya jalan akses memadai yang dapat dilewati mobil ambulan atau kendaraan pemadam kebakaran. Kondisi kerusakan jalan seperti retak atau perubahan bentuk juga bagian dari indikator kekumuhan.
Ketiga, Penyediaan Air Minum. Tidak adanya akses air minum yang aman dan berkualitas menurut standar mininum 60 liter per orang per hari menunjukkan permukiman kumuh. Penyediaan air dapat dilakukan pemerintah atau kelompok masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Keempat, Drainase Lingkungan. Kekumuhan terjadi apabila tidak terdapat drainase lingkungan yang berfungsi, drainase rusak, atau hanya berupa galian tanah. Genangan air setinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam di satu titik juga termasuk kawasan kumuh walaupun drainase lengkap.
Kelima, Pengelolaan Air Limbah. Jika sistem pengelolaan limbah tidak memenuhi persyaratan teknis seperti tidak adanya kloset leher angsa dan tangki septik baik individual maupun komunal, permukiman dikategorikan kumuh. Contohnya adalah limbah yang langsung dibuang ke drainase tanpa pengolahan.
Keenam, Pengelolaan Persampahan. Kawasan kumuh tidak memiliki sarana dan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sarana meliputi tempat sampah rumah tangga, Tempat Pengumpulan Sampah (TPS), sarana pengangkut, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sistem pengelolaan mencakup pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah di lingkungan.
Ketujuh, Proteksi Kebakaran. Kekumuhan juga dilihat dari ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran. Prasarana termasuk sumber air yang cukup, jalan akses untuk kendaraan pemadam kebakaran, hidran, dan sistem perpipaan. Sarana berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kendaraan pemadam kebakaran yang dapat diakses dalam waktu singkat (5-6 menit).
Peran Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh
Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan permukiman layak huni, namun partisipasi masyarakat sangat penting. Dengan memahami kriteria permukiman kumuh, masyarakat dapat mengenali permasalahan kumuh di lingkungan tempat tinggal mereka dan membantu pemerintah mengatasi masalah tersebut. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru.
Melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat, tujuan menghadirkan kawasan pemukiman yang layak dan nyaman dapat tercapai, serta kualitas kehidupan sosial dan lingkungan dapat terus meningkat.(*)
Eka Mariya Cahyadi, S.T. adalah mahasiswa Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Ia juga merupakan anggota Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Tengah, serta aktif sebagai praktisi dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus praktisi pemberdayaan masyarakat.
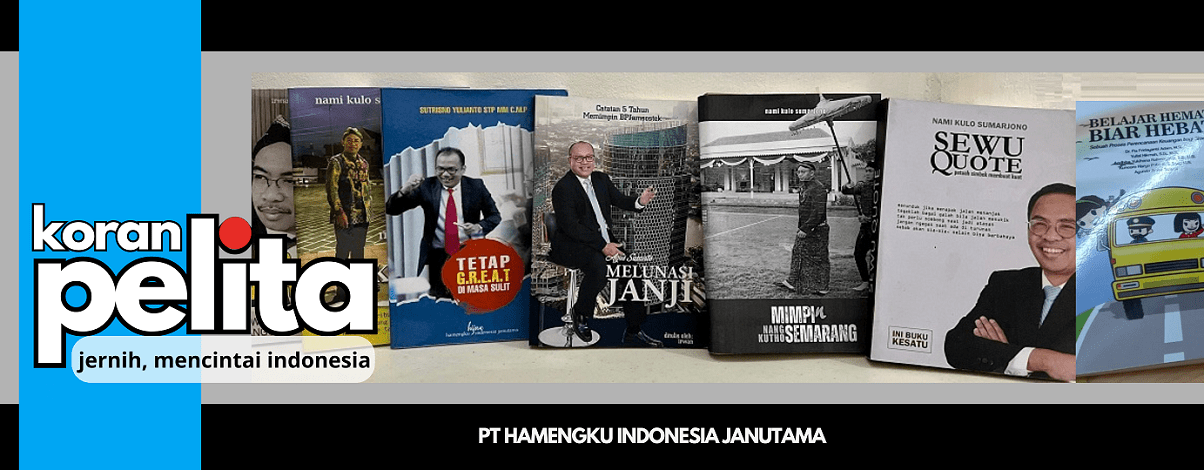 www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia






